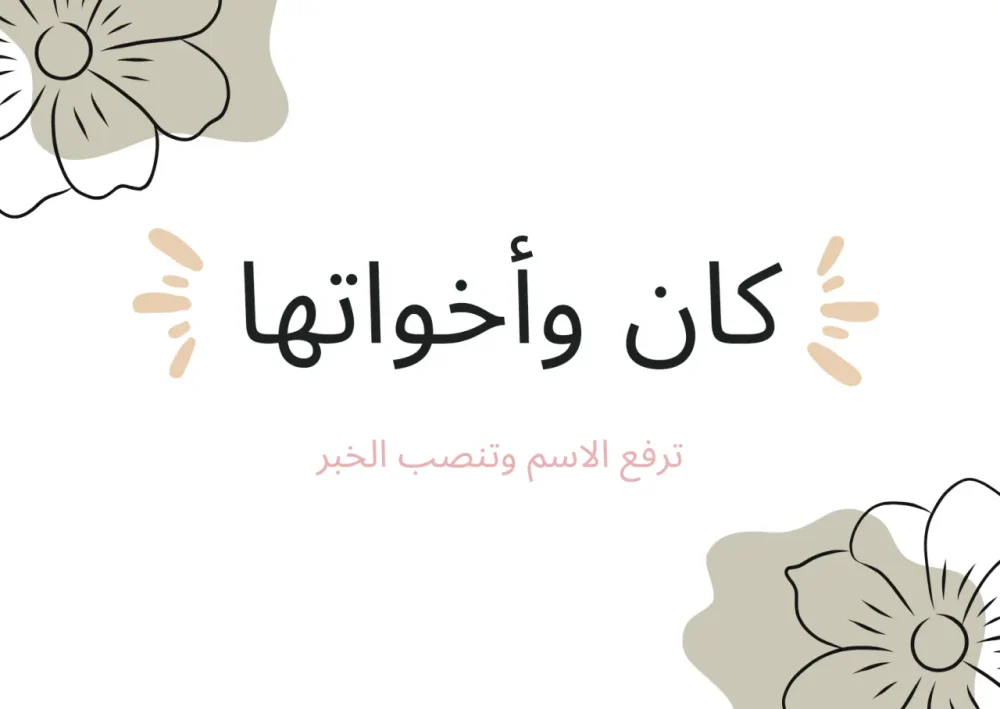Kaana wa Akhwatuha merupakan bagian dari ‘amil nawasikh yang masuk terhadap susunan mubtada khabar. Selain Kaana wa akhwatuha (كان وأخواتها), ada juga Inna wa akhwatuha (إن وأخواتها) dan Dzanna wa akhwatuha (ظن وأخواتها). Dari ketiga tersebut, dua berbentuk fi’il, yaitu kaana wa akhwatuha dan dzanna wa akhwatuha dan satu berbentuk huruf, yaitu inna wa akhwatuha. Semuanya termasuk amil nawasikh karena masuk terhadap susunan mubtada khabar dan merusak status hukum keduanya. Untuk lebih jelas, berikut penjelasan mengenai kaana wa akhwatuha:
Fungsi Kaana wa Akhwatuha (كان وأخواتها)
Kaana wa akhwatuha berfungsi “merofa’kan isim (kaana) dan menasobkan khobarnya (تَرْفَعُ الْاِسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ)”. Asal dari isim dan khobar kaana tersebut yaitu mubtada dan khobar.
Contoh:
مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ
khobar mubtada
Tambah kaana menjadi:
كَانَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلًا
khobar kaana isim kaana amil
Dari contoh tersebut, bisa kita lihat bagaimana struktur mubtada khobar berubah ketika ada tambahan كان. Pada kalimat pertama, محمد sebagai mubtada dan رسول sebagai khobar mubtada. Akan tetapi, setelah ada tambahan kaana, محمد menjadi isim kaana dan رسولا menjadi khobar kaana. Selain itu, terdapat perubahan i’rob yang terjadi pada lafadz رسول. Ketika berada pada posisi khobar mubtada, lafadz رسول beri’rob rofa’. Sedangkan ketika menjadi khobar kaana, berubah menjadi nashob (رَسُوْلًا).
Terdapat beberapa fi’il yang beramal seperti kaana. Fi’il-fi’il tersebut biasa merupakan saudara-saudara kaana (أَخْوَاتُ كَانَ), di antaranya: amsa (أَمْسَى), ashbaha (أَصْبَحَ), adhha (أَضْحَى), dzalla (ظَلَّ), baata (بَاتَ), shara (صَارَ), laisa (لَيْسَ), maa zaala (مَا زَالَ), maa infakka (مَا اِنْفَكَّ), maa fatia (مَا فَتِئَ), maa bariha (مَا بَرِحَ), maa daama (مَا دَامَ).
Lafadz, Makna, dan contohnya
Dalam penggunaan kaana wa akhwatuha disesuaikan dengan konteksnya karena setiap fi’il-fi’il tersebut mempunyai makna masing-masing. Berikut makna kaana wa akhwatuha beserta contohnya:
1. كَانَ (Kaana)
Mempunyai tiga makna:
Pertama,menunjukkan “kejadian/kondisi masa lampau”, contoh : كَانَ زَيْدٌ طَالِبًا artinya “dulu zaid adalah seorang murid”.
Kedua, menunjukkan makna “kesinambungan”, contoh: كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا artinya “Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dari dulu sampai sekarang dan tak terbatas, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Ketiga, menunjukkan makna صار (menjadi), contoh: فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ (هود: 43) artinya “maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan”
2. أَمْسَى (amsa)
Mempunyai dua makna:
Pertama, makna “kejadian/kondisi di waktu sore”, contoh: أَمْسَى عَلِيٌّ دَارِسًا artinya “pada waktu sore Ali belajar”.
Kedua, menunjukkan makna صار (menjadi), contoh: أَمْسَى عَلِيٌّ طَبِيْبًا artinya “Ali menjadi seorang dokter”
3. أَصْبَحَ (ashbaha)
Mempunyai dua makna, yaitu:
Pertama, makna “kejadian/kondisi di waktu pagi”, contoh: اَصْبَحَ عَلِيٌّ دَارِسًا artinya “pada waktu pagi Ali belajar”.
Kedua, menunjukkan makna صار (menjadi), contoh: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران: 103) artinya “lalu menjadilah kamu, karena nikmat Allah SWT, orang-orang yang bersaudara”
4. أَضْحَى (adhha)
Mempunyai dua makna, yaitu:
Pertama, makna “kejadian/kondisi di waktu dluha”, contoh: أَضْحَى عَلِيٌّ آكِلًا artinya “pada waktu dluha Ali makan”.
Kedua, menunjukkan makna صار (menjadi), contoh: أَضْحَى عَلِيٌّ مُدَرِّسًا artinya “Ali menjadi seorang guru”
5. ظَلَّ (dzalla)
Mempunyai tiga makna, yaitu:
Pertama, makna “kejadian/kondisi di waktu siang”, contoh: ظَلَّ عَلِيٌّ دَارِسًا artinya “pada waktu siang Ali belajar”.
Kedua, menunjukkan makna صار (menjadi), contoh: ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا (النحل: 58)artinya “mukanya menjadi hitam”
Ketiga, menunjukkan makna بقي (tetap), contoh: ظَلَّ التِّلْمِيْذُ جَالِسًا فِيْ مَكَانِهِ artinya “murid itu tetap duduk di tempatnya”
6. بَاتَ (baata)
Mempunyai dua makna, yaitu:
Pertama, makna “kejadian/kondisi di waktu malam”, contoh: بَاتَ عَلِيٌّ سَاهِرًا artinya “pada waktu malam Ali begadang”.
Kedua, menunjukkan makna صار (menjadi), contoh: بَاتَ بَكْرٌ مُهَنْدِسًاartinya “bakri menjadi seorang insinyur”
7. صَارَ (shaara)
Mempunyai makna التَّحَوُّلُ (berubah atau menjadi), contoh: صَارَ مُحَمَّدٌ عَالِمًا artinya “Muhammad menjadi orang yang berilmu (‘alim)”
8. لَيْسَ (laisa)
Mempunyai makna النفي (pengingkaran), contoh: لَيْسَ عَلِيٌّ جَاهِلًا artinya “Ali bukanlah orang yang bodoh”
9. زَالَ (zaala)
Mempunyai syarat dalam penggunaannya agar bisa ber’amal seperti kaana. Syarat pertama yaitu didahului oleh nafyi, menjadi: مَا زَالَ، لَا يَزَالُ، لَمْ يَزَلْ. Makna yang terkandungnya, yaitu “masih, senantiasa, atau tak henti-hentinya”. Contohnya seperti lafad: مَا زَالَ أَحْمَدُ قَائِمًا (Ahmad masih berdiri) atau وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ (mereka senantiasa berselisih). Syarat kedua yaitu didahului oleh nahyi, menjadi: لَا تَزَلْ. Makna yang terkandungnya yaitu “jangan berhenti”. Perhatikan contoh dalam syair berikut:
صَاحِ شَمِّرْ، وَلَا تَزَلْ ذَاكِرَ الْمَوْ * تِ فَنِسْيَانُهُ ضَلَالٌ مُبِيْنٌ
“wahai sahabatku, janganlah engkau berhenti mengingat mati * karena lupa akan kematian merupakan kesesatan yang nyata”
10. انفكَّ (infakka)
Sama seperti زال harus didahului oleh nafyi atau nahyi, menjadi: مَا اِنْفَكَّ atau لَا تَنْفَكَّ. Maknanya, yaitu: “masih, senantiasa, atau tak henti-hentinya”. Perhatikan contoh berikut:
مَا اِنْفَكَّ عَلِيٌّ جَالِسًا (Ali tak henti-hentinya duduk)
لَا تَنْفَكَّ ذَاكِرَ الْمَوْتِ (kamu jangan berhenti mengingat mati)
11. فَتِئَ (fatia)
Sama seperti زال harus didahului oleh nafyi atau nahyi, menjadi: مَا فَتِئَ atau لا تَفْتَأْ. Maknanya, yaitu: “masih, senantiasa, atau tak henti-hentinya”. Perhatikan contoh:
مَا فَتِئَ مُحَمَّدٌ جَالِسًا (Muhammad tak henti-hentinya duduk)
لَا تَفْتَأْ جَالِسًا (kamu jangan berhenti duduk)
12. بَرِحَ (bariha)
Sama seperti زال harus didahului oleh nafyi atau nahyi, menjadi: مَا بَرِحَ atau لَا تَبْرَحْ. Maknanya, yaitu: “masih, senantiasa, atau tak henti-hentinya”. Perhatikan contoh beriktu:
مَا بَرِحَ مُحَمَّدٌ جَالِسًا (Muhammad tak henti-hentinya duduk)
لَا تَبْرَحْ جَالِسًا (kamu jangan berhenti duduk)
13. دَامَ (daama)
Syaratnya, yaitu harus didahului oleh ma mashdariyah (ما) menjadi ما دام. Maknanya, yaitu: “masih, tetap, terus berlangsung, atau selama”. Perhatikan contoh berikut:
مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا (Zaid tetap duduk)
(مريم: 31) وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
“dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”
Baca juga:
Isim Istifham: Pengertian, lafadz dan contohnya